Regresi yang Terapeutik
Regresi itu kembali ke yang kuno, ke kondisi archaic, yang tempo dulu. Transferens dan kontratransferens dapat dilihat sebagai bentuk-bentuk regresi. Di dalam kedua fenomena ini orang mengalami diri dan relasi sebagaimana yang pernah dialaminya dengan tokoh kunci di tempo dulu. Kendatipun dapat berkonotasi kemunduran, tetapi regresi diperlukan untuk dapat menjangkau, mengurai, dan mengubah struktur dan fungsi hemisferium kanan, belahan otak yang bekerja secara dominan dalam masa archaic setiap insan, sejak kelahirannya hingga usianya menginjak tahun ketiga. Tanpa regresi, kebiasaan mental yang patologis tidak dapat dipengaruhi padahal ia terus berpengaruh. Pada titik ini dapat terpikirkan betapa ada regresi yang terapeutik, regresi yang adaptif.
Penderitaan afektif manusia karena “cedera perpautan” (attachment trauma), menurut pengalaman Donald Kalsched, seorang terapis Jungian, dapat berupa rasa dinistakan atau derita tatkala martabat direndahkan (humiliation), rasa malu (shame), dan rasa tak berdaya (helplessness) (Kalsched, 2015). Ketiga derita afektif yang terjadi karena pengasuh utama berulang meninggalkan insan belia, mengabaikannya, tak acuh kepadanya, justru ketika availability dan responsiveness-nya sungguh dibutuhkan, itu tidak tertanggungkan. Ketiganya sedemikian berbahaya jika terasakan. Akan dapat menghancurkan self yang kala itu baru muncul dan mulai bertumbuh kembang. Maka afek nista, malu, dan tak berdaya itu dipisahkan, didisosiasikan, dari kesadaran. Hemisferium kanan melakukan disosiasi untuk menyelamatkan self yang rentan.
Namun harga yang mesti dibayar sedemikian mahal. Sang pribadi yang bertumbuh dari self yang membawa struktur dan fungsi otak kanan yang menyangga disosiasi afek adalah insan yang harus terus-menerus melakukan apa pun buat dapat menjamin disosiasi tetap berlangsung, agar humiliasi, malu, dan rasa rentan seolah tidak mengganggunya.
Sebuah cara yang acap kali diterapkan adalah peluapan amarah yang sewenang-wenang (tyrannical rage) (antara lain, lihat Schore, 2019). Manusia menjadi gampang dan berulang tersinggung dan mudah tersulut dalam amarah, bahkan dalam amuk. Amarah keras atau amuk terjadi demi tidak terlepasnya rasa terhina, tak berdaya, dan malu. Demi terus berlangsungnya disosiasi ketiga afek derita. Dapat dibayangkan betapa keadaan ini membuat sang pribadi banyak mengalami disregulasi afek yang mengacaukan kehidupannya, juga sering mendapati kesulitan relasional interpersonal dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ia akan disebut penderita intermittent explosive disorder, atau barangkali dinamai pengidap gangguan kepribadian ambang. Bisa jadi kehidupan bakal kian terhina, diresapi rasa malu dan rasa tak mampu yang makin intens. Sebuah circulus vitiosus yang tak tahu kapan bakal berakhir.
Bagaimana mencapai ketiga afek dan membebaskan mereka dari disosiasi? Relasi terapeutik pasien dan psikiater atau psikoterapis, yang terus-menerus diupayakan berlangsung sebagai right brain-to-right brain relatedness dengan kelima cara berelasi yang pernah diuraikan penulis (vide “Podcast Seksi Psikoterapi: Right Brain Psychotherapy”), suatu saat akan “terganggu”, bahkan “terbuncah keras” oleh kontratransferens terapis. Dalam relasi yang terancam mengalami ruptura karena kontratransferens terapis berbenturan dengan transferens pasien, terapis yang self-nya sudah bertumbuh kembang dengan cukup baik itu dapat segera kembali “berpijak ke bumi”, mampu meregulasi afeknya yang sempat terdisregulasi, lantas mengulurkan negosiasi yang empatik kepada pasien. Uluran negosiasi yang empatik ini akan dapat meregulasi afek pasien yang terbuncah berat karena humiliasi, malu, dan helplessness yang semula dikurung hampir sempurna dalam disosiasi, kini terlepas karena pasien beregresi sesudah kena hantaman berat kontratransferens terapis. Regresi menempatkan pasien pada “titik nol” bersama terapis yang empatik, available, dan responsive. Hal ini mungkin akan menjadi pengalaman pertama bagi pasien, karena sebelumnya ia selalu dapat menghindar dari regresi berkat penjagaan ketat yang dilakukan oleh defensi disosiasi yang diperkuat dengan eksternalisasi amarah yang tiranis. Pengalaman baru itu membebaskan oksitosin dan mengurangi kortisol, mengantar pasien ke kondisi afek yang teregulasi dengan baik. Jika karena terapi yang terus berlangsung dalam aliansi terapeutik yang bagus, pada suatu saat dengan spontan tercetus lagi mutual regression dalam konstelasi transferens-kontratransferens, maka pengalaman serupa bakal berlangsung: pasien kembali mengalami perubahan dari kondisi severely dysregulated ke kondisi regulated yang makin terapeutik. Struktur hemisferium kanan yang dulu menyangga dan mempertahankan kebiasaan berdisosiasi dan mengeksternalisasi amuk, kini berubah menjadi struktur yang menyangga dan mempertahankan fungsi affect regulation yang senantiasa dibutuhkan untuk beradanya kondisi mental yang sehat. (Limas Sutanto)
Link Partner
Peranan Psikiater Dalam Kasus Hukum
Psikiater memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sebuah kasus hukum, baik untuk membuat visum et repertum maupun sebagai saksi ahli. Psikiater yang mengkhususkan diri pada hal tersebut, disebut psikiater forensik atau konsultan forensik. #psikiater #forensik #pdskji #pdskjiindonesia #dokter #kasushukum #kesehatan #kesehatanmental #pengadilan #dokterspesialis
https://www.instagram.com/reel/Cqt5XUiO4Ug/?igshid=MDJmNzVkMjY=Skizofrenia dapat disembuhkan, apakah benar?
Paradigma pengobatan skizofrenia saat ini telah bergeser, termasuk pemilihan terapi antipsikotik injeksi atau disebut atypical antipsychotic long-acting injectable (aLAI). Yuk, ikuti e-Course CEGAH KAMBUH SKIZOFRENIA terbaru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan orang dengan skizofrenia! GRATIS! Dapatkan 6 SKP IDI serta Sertifikat PDSKJI Tanpa biaya! e-Course ini dipersembahkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) bekerja sama dengan Alomedika serta didukung sepenuhnya oleh Johnson & Johnson.
KLIK link ini! https://alomedika.onelink.me/qZen/92164225Cari Dokter
Login Member
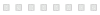
Event Yang Akan Datang
Tidak Ada Event Terbaru
Video Terbaru
Copyright © 2014 - PDSKJI - All rights reserved. Powered By Permata Technology




